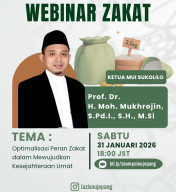Oleh: Gus Moh. Saifa Abudillah
Dewan Pengasuh Ponpes Mathali'ul Anwar Al-Islami
AKHIR-akhir ini, pesantren kerap menjadi sasaran ujaran kebencian dari sejumlah pihak—baik individu, kelompok, maupun media—yang tampak tidak senang dengan keberadaan pesantren yang telah berabad-abad menjadi bagian dari sejarah dan kebudayaan Nusantara.
Opini publik yang diarahkan dengan narasi negatif seringkali disebarkan tanpa disertai latar belakang yang memadai ataupun observasi langsung terhadap kehidupan nyata masyarakat pesantren.
Ironisnya, banyak dari pihak yang mengkritik tersebut tidak memiliki pengalaman sebagai santri atau bagian dari komunitas pesantren. Akibatnya, informasi yang mereka sampaikan menjadi bias, menyesatkan, dan cenderung menimbulkan citra buruk terhadap kehidupan pesantren.
Lebih jauh lagi, framing negatif itu biasanya dibuat tanpa dasar pengetahuan yang mendalam. Karena itu, menurut penulis—sebagai bagian dari masyarakat pesantren—akan jauh lebih bijak jika penilaian terhadap pesantren didasarkan pada sudut pandang ilmiah dan literatur yang memadai.
Secara umum, framing buruk yang sering diarahkan kepada pesantren dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal berikut:
1. Penghormatan yang Dianggap Berlebihan
Salah satu tuduhan yang sering muncul adalah bahwa bentuk penghormatan di pesantren dianggap berlebihan. Untuk menilai hal ini, kita perlu menentukan terlebih dahulu ukuran yang digunakan: apakah berdasarkan sudut pandang agama, etika, atau sosial.
Dari perspektif agama, penghormatan dianggap berlebihan (haram) jika termasuk pada dua kategori:
- Bentuk penghormatan yang secara tegas dilarang pada masa Nabi, seperti sujud; dan
- Bentuk penghormatan yang tidak dilakukan oleh Nabi maupun para sahabat.
Bentuk penghormatan seperti sujud memang dilarang karena menyerupai ibadah, meskipun sebagian ulama menilainya hanya makruh. Sedangkan penghormatan yang dilakukan oleh sahabat kepada Nabi—seperti berdiri, mencium tangan, atau lutut—dihukumi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib dalam kondisi tertentu selama tidak menimbulkan fitnah.
Adapun bentuk penghormatan yang tidak dilakukan pada masa Nabi tetapi dilakukan untuk menghormati ulama atau orang saleh, tetap diperbolehkan selama niatnya murni untuk menghormati, bukan mengkultuskan.
Dengan demikian, bentuk penghormatan yang dilakukan di pesantren—seperti mencium tangan atau berdiri menyambut kiai—masih berada dalam batas yang diperbolehkan agama.
Jika dilihat dari kacamata etika, penghormatan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kultur Nusantara yang menanamkan nilai sopan santun dan penghargaan terhadap orang yang lebih tua atau berilmu. Tradisi ini tidak bertentangan dengan norma sosial maupun aturan negara. Bahkan, mencela atau merendahkan suatu kelompok masyarakat dapat dikenai sanksi hukum sesuai undang-undang.
Sebagai subkultur dalam masyarakat Indonesia, pesantren memiliki tata nilai dan tradisi sendiri. Maka cara santri mengekspresikan rasa hormatnya—seperti mencium tangan dengan cara berjinjit—adalah bentuk adab, bukan penyembahan. Menuduh pesantren tidak menghargai martabat manusia justru menunjukkan ketidakpahaman terhadap kultur pesantren itu sendiri.
2. Tuduhan Feodalisme di Pesantren
Tuduhan berikutnya adalah bahwa pesantren menganut sistem feodal. Pandangan ini jelas perlu diluruskan. Dalam sistem feodalisme, terdapat hubungan vertikal yang kaku antara atasan dan bawahan, di mana bawahan harus tunduk sepenuhnya tanpa ruang untuk kritik.
Namun, sistem seperti itu tidak berlaku di pesantren. Kepatuhan santri kepada kiai bukanlah bentuk penundukan mutlak, melainkan bagian dari adab dan penghormatan kepada guru yang telah mencurahkan waktu dan tenaga untuk mendidik. Dalam ajaran Islam, kepatuhan kepada makhluk tidak boleh bertentangan dengan syariat Allah.
Selain itu, pesantren justru terbuka terhadap kritik dan masukan dari wali santri, alumni, maupun masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren bukan lembaga yang menutup diri, apalagi feodal. Nilai kepatuhan yang dijunjung di pesantren adalah bagian dari pendidikan moral—sesuatu yang sangat penting di tengah menurunnya etika generasi muda saat ini.
Oleh karena itu, framing yang menyebut pesantren sebagai lembaga feodal jelas tidak berdasar dan bertentangan dengan realitas di lapangan.
3. Tradisi Sowan, Memberi Uang Saat Salaman, dan Ro’an (Khidmah)
Framing negatif juga muncul terhadap tradisi sowan (menghadap kiai), memberikan uang saat bersalaman, serta ro’an atau khidmah (membantu dalam urusan kebersihan, pembangunan, dan kegiatan pesantren).
Dalam pandangan masyarakat pesantren, sowan merupakan bentuk silaturahmi antara santri, alumni, dan kiai. Tujuannya beragam—mulai dari meminta nasihat, mencari solusi atas permasalahan hidup, hingga sekadar tabarruk (memohon keberkahan). Tradisi seperti ini memiliki landasan kuat dalam sunnah para sahabat, yang juga mendatangi Nabi atau sahabat lain untuk meminta doa dan nasihat.
Memberi uang saat bersalaman dipahami sebagai bentuk sedekah yang sangat dianjurkan. Hal ini juga disebutkan dalam berbagai kitab klasik seperti Ta’lim al-Muta’allim dan Bughyatul Musytarsyidin.
Sementara itu, tradisi ro’an atau khidmah mencerminkan semangat gotong royong—nilai yang sangat dijunjung dalam Islam dan budaya Indonesia. Dalam sejarah, para sahabat juga bergotong royong membangun Masjid Quba’ bersama Nabi. Maka, membantu kebersihan dan pembangunan pesantren bukanlah bentuk eksploitasi, melainkan praktik sosial yang mendidik santri untuk berkontribusi dan bekerja sama.
Dari sisi sosial, tradisi-tradisi ini merupakan warisan budaya yang memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Menjaganya adalah bagian dari tanggung jawab moral dan kultural. Sebaliknya, merendahkan atau melecehkan tradisi tersebut merupakan tindakan yang salah secara moral, etika, maupun agama.
Penutup
Dari uraian di atas, jelas bahwa framing negatif terhadap dunia pesantren muncul karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mendalam tentang kultur pesantren itu sendiri. Pesantren bukanlah lembaga feodal, bukan pula tempat praktik penghormatan berlebihan, tetapi ruang pendidikan moral, spiritual, dan sosial yang membentuk karakter bangsa.
Oleh karena itu, perlu sikap bijak dan objektif dalam menilai pesantren—bukan dengan kebencian, melainkan dengan pemahaman yang berlandaskan ilmu dan kearifan.
Yaman, 19 Oktober 2025.
Editor : Alim Perdana