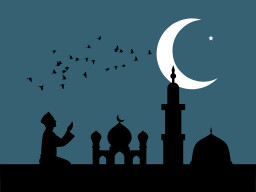Oleh: Eddy Prastyo
DI balik setiap keputusan kekuasaan, selalu ada ruang tafsir yang tak terjangkau oleh pernyataan resmi. Terutama jika keputusan itu bersentuhan dengan dua wilayah paling sensitif dalam politik: kekuasaan simbolik dan geografi kekuasaan.
Penugasan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia untuk secara aktif “berkantor” dan menangani langsung isu-isu strategis Papua dalam beberapa pekan terakhir menjadi titik temu dari keduanya.
Narasi yang dibangun secara resmi adalah narasi teknokratis: Wapres, dalam hal ini Gibran Rakabuming Raka, diberi mandat untuk mempercepat pembangunan dan memastikan agenda-agenda strategis nasional di Papua berjalan efektif.
Namun dalam lanskap komunikasi publik, narasi resmi itu ternyata tidak berdiri sendiri. Ia beradu dengan berbagai pembacaan alternatif, yang secara samar namun tegas menyuarakan kemungkinan adanya agenda tersembunyi di balik penugasan ini. Agenda yang tidak sekadar administratif, tapi politis.
Membaca Suara Publik: Resonansi di Media Massa dan Media Sosial
Untuk memahami bagaimana publik merespons isu ini, dilakukan pelacakan dan analisis atas percakapan di media massa daring dan media sosial selama tujuh hari terakhir.
Analisis ini tidak hanya dilakukan secara manual atau berbasis intuisi jurnalistik, melainkan didukung oleh keterlibatan sistem Artificial Intelligence (AI) dengan personalisasi bernama "Malala" yang saya gunakan sebagai mitra intelektual dan asisten pengolah wacana.
Metodologi Kolaboratif: Mengukur “Suara Sosial” Bersama AI
Pengumpulan data dilakukan secara kolaboratif antara saya (penulis) dan asisten AI berbasis model GPT-4o dari OpenAI. Dengan bantuan AI, saya mampu:
• Melakukan pelacakan keyword tematik secara real-time, termasuk “Wapres Papua”, “penugasan Gibran”, “pengucilan politik”, “Wapres diungsikan”.
• Memetakan distribusi dan frekuensi munculnya narasi tertentu di media sosial dan media daring dalam periode 7 hari terakhir.
• Melakukan analisis sentimen kualitatif dengan bantuan machine learning, lalu mengkontekstualisasikannya secara manual-reflektif dalam kerangka teori sosial-politik.
• Menyaring secara sistematis mana wacana yang bersifat organik dari publik, mana yang merupakan framing dari media, dan mana yang muncul dari akun-akun politis atau ideologis.
Dengan pendekatan ini, pembacaan terhadap “suara sosial” bukan sekadar opini, tapi hasil dari interaksi manusia dan mesin yang mencoba menangkap denyut wacana publik secara lebih luas, cepat, dan terverifikasi.
DISCLAIMER
Namun perlu ditegaskan: seluruh analisis ini hanya mencerminkan suara yang terekspresi secara terbuka di ruang digital, yakni media daring, media sosial, blog, dan forum publik.
Ia tidak mencerminkan keseluruhan pendapat publik Indonesia secara representatif, apalagi suara-suara diam yang tidak mengekspresikan pandangannya di ruang publik (silent majority).
Temuan ini bukan hasil survei kuantitatif atau polling dengan sampling statistik, melainkan hasil observasi dan klasifikasi narasi sosial yang tumbuh secara organik.
Hasil Analisis: Pembagian Sentimen Media Massa vs Media Sosial
1. Di Media Massa
Dari 32 artikel yang dianalisis dari media seperti Kompas, Detik, Tempo, CNN Indonesia, dan CNA Indonesia, ditemukan sentimen sebagai berikut:
• Positif (70%): Framing penugasan sebagai bentuk keseriusan negara menangani Papua.
• Netral (25%): Mengangkat isu teknis tanpa menyentuh aspek politis.
• Negatif (5%): Hanya beberapa kutipan pengamat, bukan narasi utama redaksi.
2. Di Media Sosial & Forum Digital
Dari sekitar 3.000 mention yang terdeteksi:
• Positif (±45%): Mendukung penugasan sebagai gestur empatik.
• Netral (±35%): Menyuarakan pertanyaan tentang durasi, mekanisme, dan efektivitas.
• Negatif-kritis (±20%): Muncul narasi pengucilan, pengasingan, bahkan pembungkaman politik.
Dari yang negatif, sekitar 120–150 mention secara eksplisit menggunakan frasa seperti “dijauhkan dari pusat kekuasaan”, “dipinggirkan”, atau “strategi menghilangkan fungsi politik Wapres”.
Narasi ini konsisten walaupun tidak dominan—namun mengindikasikan resonansi bawah tanah dari publik yang mencurigai simbolisme kekuasaan.
Mengapa Tafsir Ini Tumbuh? Sebuah Penjelasan Teoretis yang Terintegrasi
Framing media arus utama yang terlalu normatif justru mendorong munculnya ruang alternatif interpretasi publik. Di sinilah teori "framing" (Entman, 1993) bekerja: masyarakat tidak hanya menilai apa yang ditampilkan, tapi juga apa yang disembunyikan.
Kekosongan dalam menjelaskan sisi politik dari penugasan Wapres, justru memantik kecurigaan kolektif yang dibentuk dari pengalaman historis terhadap dinamika kekuasaan.
Lebih jauh, dalam perspektif "dramaturgi politik" (Goffman, 1959), publik tahu bahwa yang tampil di panggung depan hanyalah sebagian dari cerita.
Mereka belajar bahwa “berkantor di Papua” bisa dibaca bukan sebagai kepercayaan, tapi mungkin sebagai depolitisasi halus terhadap seorang figur yang tidak dikehendaki ikut dalam orbit kekuasaan pusat.
Sementara itu, "spiral of silence" (Noelle-Neumann, 1974) menjelaskan kenapa narasi ini tetap minor. Karena media besar tidak memberi ruang eksplisit bagi tafsir tersebut, maka mereka yang percaya pada narasi “pengucilan politik” memilih menyuarakannya dalam kanal-kanal terbuka dan tidak terafiliasi, seperti Twitter, komentar blog, dan grup anonim. Mereka mungkin kecil secara jumlah, tapi tajam dalam framing dan konsisten dalam tafsir.
Ketiga pendekatan ini saling menyatu: framing membuka ruang tafsir, dramaturgi memberi lapisan makna simbolik, dan spiral of silence menjelaskan mengapa suara-suara itu hidup di pinggir dan bukan di tengah.
Refleksi: Antara Dikirim atau Disingkirkan
Sebagai pengamat yang cukup lama menyelami bagaimana narasi kekuasaan dibentuk, saya meyakini bahwa kekuasaan tidak pernah hanya bekerja secara eksplisit. Ia bekerja dalam simbol, dalam gesture, dalam pemilihan tempat, dalam penugasan.
Penugasan Wapres ke Papua, secara administratif bisa saja logis. Tapi dalam kontestasi kekuasaan, logika administratif tidak selalu steril dari motif politis. Di negeri ini, pemindahan jabatan sering kali bukan untuk mendekatkan seseorang ke rakyat, tapi untuk menjauhkannya dari perebutan pengaruh.
Maka ketika publik menaruh tafsir “pengucilan politik”, itu bukan delusi. Itu bentuk kewaspadaan historis. Kewaspadaan terhadap bagaimana kekuasaan bersandiwara, dan bagaimana publik kini belajar menonton bukan hanya aktor utama, tetapi bagaimana sutradaranya menyusun panggung.
Papua memang jauh secara geografis. Tapi dalam geografi politik, jarak bisa berarti jeda pengaruh. Dan jeda, kalau disematkan dengan manis, bisa terlihat seperti pengabdian.
Eddy Prastyo | Editor in Chief | Suara Surabaya Media
“Membaca kekuasaan bukan dari apa yang dikatakan, tapi dari apa yang sengaja tak dijelaskan.”
Editor : Alim Perdana